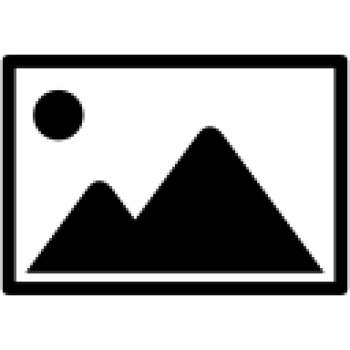Ekspor Turunan CPO Indonesia Kalah Bersaing dengan Malaysia
16 Februari 2011
Admin Website
Artikel
5798
JAKARTA--MICOM: Sebagai produsen crude palm oil (CPO) terbesar
dunia, Indonesia masih belum bisa mengalahkan Malaysia dalam jumlah
ekspor hasil industri turunan produk tersebut.
Pada 2010, dari total produksi sekitar 15,6 juta ton CPO, Indonesia hanya mengekspor sekitar 6,8 juta ton produk turunan. Sementara sisanya, sebesar 8,8 juta ton diekspor dalam bentuk minyak mentah.
Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Fadhil Hasan menyatakan, sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir perkembangan produk turunan CPO di Indonesia semakin membaik, tetapi tidak secepat yang diharapkan. Menurutnya, lambatnya pertumbuhan industri turunan CPO terkendala sejumlah kebijakan pemerintah.
"Industri turunan sudah ada perkembangan. Namun jika dibandingkan dengan Malaysia kita masih tertinggal jauh. Kami masih belum puas karena tidak secepat yang diharapkan. Perbandingan ekspor CPO dengan produk turunannya masih 60:40. Harus ada kondisi yang kondusif untuk pengembangan hilir, yaitu melalui kebijakan insentif," ujarnya dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (14/2).
Salah satu kebijakan yang masih menjadi kendala adalah bea keluar (BK) ekspor produk sawit yang diterapkan secara progresif. Menurutnya, BK progresif tidak tepat lagi diterapkan karena telah melenceng dari tujuan awalnya untuk menstabilkan harga minyak goreng dalam negeri. Lantaran itu, kebijakan tersebut dinilai tidak efektif mendorong hilirisasi industri kelapa sawit.
"Saat ini BK progresif sudah menjadi instrumen penerimaan negara, tidak seperti tujuan awalnya untuk menstabilkan harga minyak goreng di dalam negeri. Karena itu, kami sudah sampaikan usulan ke pemerintah untuk terapkan BK flat 3% kalau harga CPO di atas US$ 700 per ton. Kami yakin, ini bisa stabilkan harga minyak goreng sekaligus mendorong tumbuhnya industri turunan CPO," jelasnya.
Selain itu, tambah Fadhil, penerapan BK progresif hanya akan membuat harga sawit di tingkat petani melorot karena memengaruhi harga tandan buah segar (TBS) sawit. Ia mencontohkan, saat diterapkan BK sebesar 3%, penurunan harga CPO di tingkat petani sekitar Rp 195 per kilogram, sementara ketika BK yang diterapkan sebesar 7,5% maka penurunan harga meningkat menjadi Rp560 per kilogram.
"Karena itu, kami minta pemerintah agar mengevaluasi kembali skema BK ekspor CPO ini. Seharusnya dana BK tidak menjadi instrumen penerimaan negara, tapi dikembalikan ke petani untuk membantu peremajaan tanaman kelapa sawit, membangun infrastruktur di areal perkebunan, atau dana subsidi untuk meredam kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri," paparnya.
Selain BK, menurut Fadhil, persoalan lain yang juga masih menghambat pertumbuhan ekspor CPO Indonesia adalah belum tuntasnya perundingan Preferential Trade Agreement (PTA) dengan Pakistan. Ia menilai, berlarut-larutnya perundingan itu membuat pasar ekspor sawit mentah Indonesia di Pakistan semakin tergerus karena kalah bersaing dengan produk CPO Malaysia.
"Malaysia sudah punya kesepakatan sejenis. Karena itu mereka bisa dapatkan bea masuk yang lebih rendah. Implikasinya, tentu harga kita kalah bersaing di pasar Pakistan karena harga CPO Malaysia lebih murah dibandingkan harga CPO Indonesia. Ini akibat perundingan yang berlarut-larut. Sangat disayangkan jika tidak segera dituntaskan," tukasnya.
Menurut dia, pada 2007 Indonesia mengekspor sekitar US$567 juta ke Pakistan. Namun kini, nilai ekspor CPO Indonesia ke Pakistan turun menjadi hanya sekitar puluhan ribu dollar AS karena perundingan perjanjian yang belum dituntaskan. Selain itu, pangsa pasar produk CPO nasional di Pakistan turun dari 45% menjadi sekitar 11%.
"Hambatannya karena Kementerian Pertanian (Kementan) masih keberatan dengan permintaan Pakistan untuk menghapus bea masuk impor jeruk kino Pakistan. Kementan melihat produk jeruk impor dari China saja sudah sudah ditetapkan bea 0%, takutnya jika jeruk kino juga, maka itu akan mengganggu petani kita," jelasnya.
Selain itu, tambah dia, Pakistan juga meminta pemerintah Indonesia membebaskan bea masuk impor sejumlah produk lainnya sebagai konsekuensi penurunan bea masuk produk sawit nasional ke negara tersebut. Namun, menurut perhitungan Fadhil, Indonesia tidak akan mengalami kerugian apapun jika memenuhi permintaan tersebut.
"Saya pikir jika dihitung-hitung antara nilai bea impor terhadap sejumlah produk yang Pakistan ingin kita bebaskan dibandingkan nilai ekspor kita, itu tidak ada artinya. Jadi tidak apa-apa seharusnya kalau pemerintah Indonesia penuhi permintaan itu. Imbalan yang akan kita terima jauh lebih besar," imbuhnya.
Sementara itu, selain mengkritisi penerapan BK progresif, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) juga mengeluhkan banyaknya pungutan yang harus disetorkan produsen kelapa sawit nasional. Sekjen Apkasindo Asmar Arsyad menilai, banyaknya pungli tidak hanya merugikan produsen, tapi juga para petani kecil.
"Efeknya domino kalau produsen kena pungutan, kita juga kena imbasnya, salah satunya posisi tawar harga jual TBS ke produsen menjadi kecil. Pungutannya bermacam-macam, dari yang resmi sampai yang liar atau pungli, seperti uang keamanan dan lainnya. Sementara pungutan resmi datangnya ya dari perda-perda itu," jelasnya.
Ia mencontohkan, adanya pungutan untuk jaminan keamanan selama tiga tahun sebesar Rp400 juta. Belum lagi jenis-jenis biaya lain yang juga harus disetorkan. Menurut Asmar, nilai pungutan itu jika dijumlahkan bisa mencapai 50% pendapatan usaha yang dihasilkan produsen. Lantaran itu, ada kecenderungan produsen sawit enggan membayarkan pajaknya.
"Produsen pikir lebih baik bayar orang untuk gelapkan pajak daripada harus keluarkan uang hingga 50% pendapatan usaha. Kebijakan-kebijakan seperti ini yang harus segera dibereskan kalau mau mendorong pertumbuhan industri sawit nasional," tandasnya.
Pada 2010, dari total produksi sekitar 15,6 juta ton CPO, Indonesia hanya mengekspor sekitar 6,8 juta ton produk turunan. Sementara sisanya, sebesar 8,8 juta ton diekspor dalam bentuk minyak mentah.
Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Fadhil Hasan menyatakan, sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir perkembangan produk turunan CPO di Indonesia semakin membaik, tetapi tidak secepat yang diharapkan. Menurutnya, lambatnya pertumbuhan industri turunan CPO terkendala sejumlah kebijakan pemerintah.
"Industri turunan sudah ada perkembangan. Namun jika dibandingkan dengan Malaysia kita masih tertinggal jauh. Kami masih belum puas karena tidak secepat yang diharapkan. Perbandingan ekspor CPO dengan produk turunannya masih 60:40. Harus ada kondisi yang kondusif untuk pengembangan hilir, yaitu melalui kebijakan insentif," ujarnya dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (14/2).
Salah satu kebijakan yang masih menjadi kendala adalah bea keluar (BK) ekspor produk sawit yang diterapkan secara progresif. Menurutnya, BK progresif tidak tepat lagi diterapkan karena telah melenceng dari tujuan awalnya untuk menstabilkan harga minyak goreng dalam negeri. Lantaran itu, kebijakan tersebut dinilai tidak efektif mendorong hilirisasi industri kelapa sawit.
"Saat ini BK progresif sudah menjadi instrumen penerimaan negara, tidak seperti tujuan awalnya untuk menstabilkan harga minyak goreng di dalam negeri. Karena itu, kami sudah sampaikan usulan ke pemerintah untuk terapkan BK flat 3% kalau harga CPO di atas US$ 700 per ton. Kami yakin, ini bisa stabilkan harga minyak goreng sekaligus mendorong tumbuhnya industri turunan CPO," jelasnya.
Selain itu, tambah Fadhil, penerapan BK progresif hanya akan membuat harga sawit di tingkat petani melorot karena memengaruhi harga tandan buah segar (TBS) sawit. Ia mencontohkan, saat diterapkan BK sebesar 3%, penurunan harga CPO di tingkat petani sekitar Rp 195 per kilogram, sementara ketika BK yang diterapkan sebesar 7,5% maka penurunan harga meningkat menjadi Rp560 per kilogram.
"Karena itu, kami minta pemerintah agar mengevaluasi kembali skema BK ekspor CPO ini. Seharusnya dana BK tidak menjadi instrumen penerimaan negara, tapi dikembalikan ke petani untuk membantu peremajaan tanaman kelapa sawit, membangun infrastruktur di areal perkebunan, atau dana subsidi untuk meredam kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri," paparnya.
Selain BK, menurut Fadhil, persoalan lain yang juga masih menghambat pertumbuhan ekspor CPO Indonesia adalah belum tuntasnya perundingan Preferential Trade Agreement (PTA) dengan Pakistan. Ia menilai, berlarut-larutnya perundingan itu membuat pasar ekspor sawit mentah Indonesia di Pakistan semakin tergerus karena kalah bersaing dengan produk CPO Malaysia.
"Malaysia sudah punya kesepakatan sejenis. Karena itu mereka bisa dapatkan bea masuk yang lebih rendah. Implikasinya, tentu harga kita kalah bersaing di pasar Pakistan karena harga CPO Malaysia lebih murah dibandingkan harga CPO Indonesia. Ini akibat perundingan yang berlarut-larut. Sangat disayangkan jika tidak segera dituntaskan," tukasnya.
Menurut dia, pada 2007 Indonesia mengekspor sekitar US$567 juta ke Pakistan. Namun kini, nilai ekspor CPO Indonesia ke Pakistan turun menjadi hanya sekitar puluhan ribu dollar AS karena perundingan perjanjian yang belum dituntaskan. Selain itu, pangsa pasar produk CPO nasional di Pakistan turun dari 45% menjadi sekitar 11%.
"Hambatannya karena Kementerian Pertanian (Kementan) masih keberatan dengan permintaan Pakistan untuk menghapus bea masuk impor jeruk kino Pakistan. Kementan melihat produk jeruk impor dari China saja sudah sudah ditetapkan bea 0%, takutnya jika jeruk kino juga, maka itu akan mengganggu petani kita," jelasnya.
Selain itu, tambah dia, Pakistan juga meminta pemerintah Indonesia membebaskan bea masuk impor sejumlah produk lainnya sebagai konsekuensi penurunan bea masuk produk sawit nasional ke negara tersebut. Namun, menurut perhitungan Fadhil, Indonesia tidak akan mengalami kerugian apapun jika memenuhi permintaan tersebut.
"Saya pikir jika dihitung-hitung antara nilai bea impor terhadap sejumlah produk yang Pakistan ingin kita bebaskan dibandingkan nilai ekspor kita, itu tidak ada artinya. Jadi tidak apa-apa seharusnya kalau pemerintah Indonesia penuhi permintaan itu. Imbalan yang akan kita terima jauh lebih besar," imbuhnya.
Sementara itu, selain mengkritisi penerapan BK progresif, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) juga mengeluhkan banyaknya pungutan yang harus disetorkan produsen kelapa sawit nasional. Sekjen Apkasindo Asmar Arsyad menilai, banyaknya pungli tidak hanya merugikan produsen, tapi juga para petani kecil.
"Efeknya domino kalau produsen kena pungutan, kita juga kena imbasnya, salah satunya posisi tawar harga jual TBS ke produsen menjadi kecil. Pungutannya bermacam-macam, dari yang resmi sampai yang liar atau pungli, seperti uang keamanan dan lainnya. Sementara pungutan resmi datangnya ya dari perda-perda itu," jelasnya.
Ia mencontohkan, adanya pungutan untuk jaminan keamanan selama tiga tahun sebesar Rp400 juta. Belum lagi jenis-jenis biaya lain yang juga harus disetorkan. Menurut Asmar, nilai pungutan itu jika dijumlahkan bisa mencapai 50% pendapatan usaha yang dihasilkan produsen. Lantaran itu, ada kecenderungan produsen sawit enggan membayarkan pajaknya.
"Produsen pikir lebih baik bayar orang untuk gelapkan pajak daripada harus keluarkan uang hingga 50% pendapatan usaha. Kebijakan-kebijakan seperti ini yang harus segera dibereskan kalau mau mendorong pertumbuhan industri sawit nasional," tandasnya.
DIKUTIP DARI MEDIA INDONESIA, SENIN, 14 PEBRUARI 2011